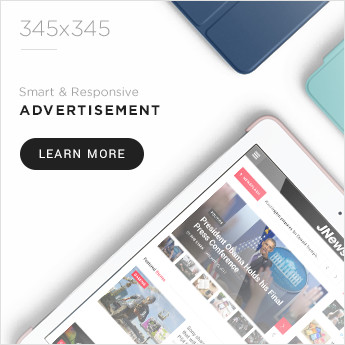LUMAJANG (PI) – Pagi di lereng Gunung Lemongan selalu tiba dengan cara yang lembut. Embun menggantung di daun pinang, angin berembus pelan, dan cahaya matahari menyelinap di antara batang-batang tegak yang kini berdiri kokoh. Di sanalah Daim sering berhenti sejenak, menatap hutan yang hari ini hijau, seolah sedang bercermin pada masa lalu.
Tak banyak yang tahu, puluhan tahun silam kawasan ini pernah nyaris kehilangan harapan. Lereng yang kini rimbun dulunya gersang, tanahnya retak, air hujan turun tanpa penahan. Di tengah keadaan itulah Daim berdiri sendirian, percaya bahwa alam masih bisa diselamatkan, meski tak ada yang ikut percaya.
Daim bukan akademisi, bukan pejabat, apalagi aktivis lingkungan yang akrab dengan panggung besar. Ia hanyalah warga desa yang hidup dari alam dan belajar langsung dari perubahan-perubahan kecil di sekitarnya. Pengalamannya tak tertulis di buku, tetapi terpatri kuat dalam ingatan.
Satu peristiwa menjadi titik balik hidupnya. Banjir besar yang datang tiba-tiba menghanyutkan rumah keluarganya. Air turun dari gunung tanpa ampun. Sejak saat itu, bagi Daim, hutan bukan lagi sekadar latar kehidupan, melainkan benteng terakhir yang menentukan keselamatan banyak orang.
Ketika kebakaran hutan dan pembalakan liar merusak Gunung Lemongan, Daim memilih jalan sunyi. Pada tahun 1996, saat banyak orang mengejar hasil cepat dari kayu, ia justru memanggul ember berisi bibit, menapaki lereng curam seorang diri. Tak ada perintah, tak ada anggaran, tak ada janji hasil.
“Kalau hutannya gundul, air hujan pasti turun semua ke bawah,” katanya sederhana, seolah sedang menyampaikan hukum alam yang paling dasar.
Ia menanam dengan kesabaran yang nyaris tak masuk akal. Sirsak, kopi, alpukat, semuanya pernah dicoba. Banyak yang gagal. Bibit dimakan hewan liar, patah diterpa angin, atau mati sebelum tumbuh kuat. Hingga akhirnya, pinang bertahan.
Akar pinang mencengkeram tanah dengan kuat. Batangnya tegak, daunnya membantu menahan laju air hujan. Dari sanalah Daim menemukan harapan yang selama ini ia cari, bukan dari hasil panen, tetapi dari tanda-tanda kehidupan yang kembali.
Hari-harinya diisi dengan membuka semak, menggali tanah, dan menyusun batu demi batu agar bisa mencapai lokasi tanam. Tubuhnya lelah, tangannya kapalan, kakinya sering luka. Namun yang paling menyakitkan justru bukan rasa lelah, melainkan suara-suara sumbang dari sekitarnya.
Ia ditertawakan, disebut gila, dianggap membuang waktu. Menanam pinang dinilai tak punya nilai ekonomi. Saat harga pinang jatuh, hasil panennya bahkan tak cukup untuk membeli beras. Namun Daim tetap datang ke hutan, hari demi hari, tanpa jeda.
“Ada waktu saya hampir percaya omongan orang. Tapi waktu lihat gunung mulai hijau, hati saya tenang,” ujarnya jujur.
Bagi Daim, hijau adalah tanda kehidupan. Tanda bahwa air hujan tidak lagi turun dengan amarah. Tanda bahwa anak-anak di bawah gunung bisa tidur lebih nyenyak saat musim hujan datang tanpa ketakutan.
Tahun-tahun berlalu, dan perubahan pelan-pelan terlihat. Pinang tumbuh melingkari lereng, membentuk sabuk alami penahan erosi. Jurang yang dulu dalam mulai dangkal. Banjir tak lagi menjadi cerita tahunan yang menakutkan.
Tanpa disadari, apa yang dulu ditertawakan mulai ditiru. Ketika harga pinang membaik, warga berdatangan. Mereka menanam, memanen, dan menggantungkan hidup dari pohon-pohon yang dulu dianggap tak berharga.
Daim tak pernah merasa paling berjasa. Ia tidak marah ketika orang datang belakangan. Ia justru tersenyum melihat hutan kembali hidup. “Yang penting hutannya hidup,” katanya singkat.
Manfaat hutan pinang kini dirasakan banyak orang. Ada yang memanfaatkan pelepah, ada yang mencari pakis, ada pula yang bekerja sebagai buruh panen. Jalan setapak yang dulu Daim susun dari batu kini menjadi akses rezeki bersama.
Namun jalan sunyi itu tak selalu mulus. Niat baiknya sempat diuji oleh birokrasi. Ia diminta mengurus izin, dipertanyakan legalitasnya, bahkan hampir kehilangan kesempatan menerima penghargaan karena dianggap menanam tanpa prosedur.
Daim tak melawan, tetapi juga tak gentar. “Saya menanam supaya tidak ada bencana. Kalau ada apa-apa, kami yang pertama kena,” ucapnya mantap.
Ketulusan itu akhirnya menemukan jalannya. Pada tahun 2022, Daim menerima Kalpataru, penghargaan tertinggi bagi pejuang lingkungan. Bukan sebagai akhir perjuangan, melainkan pengakuan atas kerja sunyi yang telah lama ia lakukan.
Kini usianya tak lagi muda. Langkahnya lebih pelan, tetapi matanya tetap berbinar setiap kali berbicara tentang hutan. Ia tahu, waktunya di lereng gunung tak akan selamanya.
Pesannya sederhana, ditujukan pada generasi muda. “Tidak perlu jadi orang hebat untuk menjaga alam. Cukup mau menanam dan merawat.”
Bagi Daim, hutan adalah warisan. Dan setiap pohon pinang yang berdiri hari ini adalah bukti bahwa kesabaran, meski sering disalahpahami, pada akhirnya selalu menemukan maknanya. ADM (Sumber : Kominfo)